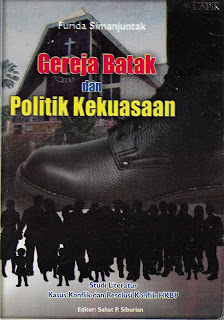Oleh: Bantors Sihombing
Setiap kali terjadi konflik dalam Gereja Batak (HKBP), penyelesaiannya tidak pernah tuntas. Jejaknya masih bisa terlihat sampai sekarang. Kadang dibiarkan berhenti dengan sendirinya, dan ada yang hanya diselesaikan di tingkat elite gereja. Ini mengakibatkan konflik dengan pola yang sama, dengan aktor yang berbeda, sering terulang.
Pada tahun 1917, HKBP mengalami suatu peristiwa konflik. Saat itu, sekelompok tokoh nasionalis Kristen Batak merasa tidak puas dengan kepemimpinan orang asing (Jerman) di HKBP. Gerakan ini dipimpin M. H. Manullang, yang mendirikan Hatopan Kristen Batak (HKB) tahun 1917. Sepuluh tahun kemudian, yakni 1927 berdiri Hoeria Christen Batak (HCB, yang sekarang menjadi HKI). Menyusul terbentuk Gereja Mission Batak (GMB) dan Punguan Kristen Batak (PKB).
Konflik dalam internal HKBP terjadi lagi pada tahun 1962. Dua tahun berikutnya, lahir gereja baru, yakni Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tahun 1964. Bibit konflik terjadi akibat pemecatan 22 pendeta, setelah HKBP menggelar Sinode Godang Istimewa untuk pertama kali, Juni dan Oktober 1962. Ini menyulut reaksi yang merembes ke persoalan-persoalan lain. Saat itu, tercatat ribuan anggota jemaat beserta pendeta, guru jemaat, dan sintua pindah ke GKPI.
Dalam situasi itu, untuk pertama kali, muncul isu sentimen kedaerahan dalam internal gereja, yakni kelompok Silindung, Humbang, Samosir, dan Toba. Walau banyak pihak mencoba menepis isu kedaerahan ini, tetapi dalam kenyataannya tak bisa dimungkiri. Bahkan, isu ini masih terus mewarnai berbagai konflik orang Batak sampai saat ini, bukan hanya di gereja, juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal politik.
Kisruh berikutnya terjadi setelah Sinode Godang, 27-31 Juni 1987, akibat persaingan Sekjen HKBP incumbent (petahana) pada saat itu Pdt. P.M Sihombing, MTh dengan Pdt. Dr. S.A.E. Nababan dalam perebutan jabatan Ephorus. Pdt. Dr. S A.E. Nababan terpilih menjadi Ephorus dan Pdt. O.P.T Simorangkir sebagai Sekjen. Masing-masing pihak saling tuding, dan memunculkan gesekan yang diikuti dengan gelombang unjuk rasa.
Konflik muncul lagi pada Sinode Godang, 23-28 Nopember 1992. Ada tiga agenda saat itu, yakni penyelesaian kemelut, periode fungsionaris dan menetapkan aturan peraturan (AD dan ART) tahun 1992-2002. Sinode berhasil membentuk tim penyelesaian kemelut dan menetapkan Aturan HKBP 1992-2002 (AD) tanpa Peraturan (ART). Sementara, pemilihan fungsionaris tidak terlaksana akibat keributan sidang sinode.
Kemudian, pemerintah melakukan campur tangan dengan menunjuk Pdt. Dr. S.M. Siahaan sebagai Pejabat Ephorus. Pejabat Ephorus, dengan dukungan pemerintah, mengundang peserta untuk mengikuti Sinode Agung Istimewa (SAI), 11-13 Pebruari 1993 di Hotel Tiara Medan. Dalam Sinode ini terpilih Pdt. Dr. P.W.T. Simanjuntak sebagai Ephorus dan Pdt. Dr. S.M. Siahaan sebagai Sekretaris Jenderal.
Sementara itu, sebagian warga dan pelayan HKBP masih mengakui Pdt. Dr. S.A.E. Nababan, LLD sebagai Ephorus yang sah. Sehingga HKBP terpecah menjadi dua kelompok yang disebut kelompok SSA/AP (pihak S.A.E. Nababan) dan kelompok SAI-Tiara (pihak P.W.T. Simanjuntak). Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1998, diwarnai berbagai bentrok fisik di antara para pendukung kedua pihak.
Tercatat beberapa orang meninggal dunia akibat konflik tersebut. Kantor Pusat HKBP dan aset strategis lainnya menjadi rebutan kedua pihak. Banyak jemaat yang terpecah dan sebagian memisahkan diri dari gereja asal, sehingga pada waktu itu berdiri jemaat-jemaat baru di pihak SSA maupun SAI. Tak sedikit pula yang pindah ke gereja lain.
Pada 26 Oktober-1 Nopember 1998 dilaksanakan Sinode Godang di Pematangsiantar dan Balige. Dalam Sinode ini terpilih Pdt. Dr. J.R. Hutauruk sebagai Pejabat Ephorus dengan tugas menyelenggarakan rekonsiliasi selambat-lambatnya enam bulan. Pdt. Dr. J.R. Hutauruk dengan cepat mengupayakan rekonsiliasi. Pada 17 Nopember 1998, Pejabat Ephorus Pdt. Dr. J.R. Hutauruk dan Ephorus Pdt. Dr. S.A.E. Nababan, LLD. menandatangani Pernyataan Bersama di Gereja HKBP Sudirman Medan.
Hal tersebut menentukan proses rekonsiliasi melalui Sinode Godang pada 18-20 Desember 1998 di Kompleks FKIP Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Sinode ini memilih Pdt. Dr. J.R. Hutauruk sebagai Ephorus dan Pdt. W.T.P. Simarmata, MA sebagai Sekretaris Jenderal. Ini menjadi titik awal penyelesaian konflik HKBP.
Masih Membekas
Terpilihnya Ephorus dan Sekjen bersama fungsionaris lainnya dianggap sudah menjadi penyelesaian konflik yang terjadi selama enam tahun. Representasi dari kedua pihak yang bertikai diakomodir dalam jabatan-jabatan yang ada. Tak heran, ada muncul tuduhan, bahwa rekonsiliasi hanya membagi-bagi jabatan di kalangan elite gereja HKBP.
Upaya rekonsiliasi (perdamaian) ditindaklanjuti dengan imbauan agar jemaat (huria) yang sempat pecah bersatu kembali. Pendeta dari masing-masing pihak sama-sama melayani, sebelum dimutasikan. Namun perlu dicatat, tidak semua jemaat mau bersatu kembali. Ada yang tetap bertahan karena telah membangun gedung gereja sendiri, dan ada pula yang memang tidak sudi lagi bergabung dengan jemaat sebelumnya.
Fakta sedemikian itu menunjukkan bahwa perdamaian di tingkat elite tak otomatis terjadi di tingkat massa (grassroot). Faktor penyebabnya antara lain karena perpecahan selama bertahun-tahun telah menjadi semacam ‘ideologi’. Suatu kelompok telah memandang kelompok lain sebagai musuh dan tak ada lagi titik temu.
Hingga kini, sadar atau tidak sadar, di kalangan warga jemaat maupun pendeta masih diidentifikasi berdasarkan pada kelompok tahun 1992-1998. Isu ini digunakan untuk merangkul teman, sekaligus untuk menyingkirkan orang yang dianggap sebagai lawan. Pada Sinode Godang 2004, 2008, dan 2012, penggalangan dukungan berdasarkan isu kelompok ini masih kuat.
Dalam tiap-tiap konflik tentu ada yang terluka, bahkan juga sengaja saling melukai. Luka seharusnya dapat disembuhkan. Luka fisik lebih mudah untuk sembuh dengan memanfaatkan jasa kedokteran modern. Tapi, tidak mudah untuk menyembuhkan luka batin, sakit hati dan kepahitan. Prosesnya memerlukan waktu dan keberanian untuk saling menyembuhkan.
Gereja Batak (HKBP) perlu memetik pelajaran berharga dari Nelson Mandela di Afrika Selatan tentang bagaimana menyembuhkan diri dan komunitasnya setelah mengalami konflik bertahun-tahun. Afrika Selatan sukses melakukan rekonsiliasi atas peran Nelson Mandela dan Desmond Tutu.
Seluruh unsur-unsur yang menjadi prasyarat rekonsiliasi dalam konteks Afrika Selatan terpenuhi. Seperti adanya proses pengungkapan kebenaran, pengakuan bersalah dari pihak pelaku, dan adanya pemberian maaf dari korban, kemudian diikuti dengan adanya rehabilitasi, amnesti, kompensasi, dan restitusi.
Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan yang terpilih melalui pemilu demokratis tahun 1994, mengajarkan pengampunan kepada dunia. Afrika Selatan telah koyak-moyak akibat politik rasial (apartheid), dan Nelson Mandela sendiri meringkuk di penjara selama 27 tahun.
Mandela mengawali upaya rekonsiliasi dengan cara yang amat khas. Pada saat pelantikannya menjadi presiden, ia meminta sipir penjara tempatnya ditahan naik ke panggung. Kemudian, ia antara lain membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC), dengan ketua Uskup Agung Desmond Tutu. Dengan tulus ikhlas, Mandela berusaha mengelakkan pola balas dendam yang dilihatnya terjadi di banyak negara, setelah ras atau suku yang semula tertindas mengambil alih pemerintahan.
Selama dua setengah tahun, penduduk Afrika Selatan menyimak berbagai laporan kekejaman melalui pemeriksaan TRC. Peraturannya sederhana: bila seorang polisi atau perwira kulit putih secara sukarela menemui pendakwanya, mengakui kejahatannya, dan mengakui sepenuhnya kesalahannya, maka polisi tersebut tidak akan diadili dan dihukum.
Pendekatan sedemikian dicela oleh penganut garis keras dan menganggapnya tidak adil karena dengan begitu saja membebaskan pelaku kejahatan. Namun, Mandela bersikukuh bahwa negera Afrika Selatan jauh lebih memerlukan kesembuhan daripada keadilan. Dengan langkah ini, Mandela juga mengimplementasikan bagaimana sebuah rekonsilasi antara rezim kulit putih yang sangat rasis harus berdamai dengan golongan masyarakat kulit hitam yang pernah ditindasnya secara keji.
Para penganut politik apartheid dituntut harus secara sukarela mengakui seluruh perbuatannya untuk mendapat pengampunan. Warga kulit hitam tidak diperbolehkan melampiaskan dendam, namun diizinkan mengobati luka dengan cara yang manusiawi. Melalui kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi selama dua tahun, masyarakat Afrika Selatan mendapatkan laporan kekejaman rezim apartheid melalui pengakuan sukarela.
Perlu Tindak Lanjut
Bagaimana dengan HKBP pascakonflik 1992-1998. Hal ini perlu diajukan karena dalam setiap konflik yang terjadi di HKBP hampir tidak ada penyelesaian secara tuntas. Jejak konflik masih bisa terlihat dan dirasakan sampai sekarang. Situasi konflik seolah dibiarkan berhenti secara alami, dengan lebih menonjolkan penyelesaian di tingkat elite gereja.
Pembiaran konflik tanpa penyelesaian yang benar akan mengakibatkan terjadinya konflik sejenis dengan pola yang sama, yang berbeda hanya aktornya. Jika tidak ada penyelesaian secara utuh dan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, maka bom waktu konflik akan senantiasa mengancam perjalanan HKBP.
Rekonsiliasi tak cukup hanya pada tingkat elite dengan komposisi bagi-bagi jabatan. Tapi mata rantai konflik harus dihentikan, jika tidak maka identifikasi atas nama kelompok masa lalu akan selalu menjadi isu penting pada setiap pergantian Ephorus. Ditularkan dari generasi ke generasi. Sehingga kalaupun tampak tenang di permukaan, namun sesewaktu bisa meledak.
Seharusnya HKBP mengerti benar prinsip dasar rekonsiliasi: Tak ada pengampunan tanpa diawali pengakuan! Prinsip ini terinsiprasi dari pesan Alkitab: “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” (1 Yohanes 1:9). Prinsip inilah yang diterapkan di Afrika Selatan, sehingga proses rekonsiliasi berhasil.
Jadi harus ada proses pengungkapan kebenaran, pengakuan bersalah, dan pemberian maaf. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi, amnesti, kompensasi, serta restitusi. Hal ini dilakukan bukan hanya di tingkatan pimpinan, tapi ke seluruh jemaat. Dengan menyadari kesalahan, belajar dari kesalahan dan bertekad tidak mengulanginya lagi akam membuat HKBP semakin tahan menyikapi terpaan konflik yang mengancam keutuhan gereja.
Langkah Awal
Pembahasan tentang konflik HKBP 1992-1998 sudah banyak dilakukan. Namun hanya sedikit yang memotret secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan penulis hanya mengacu pada data dan informasi dari satu pihak saja sehingga pembahasannya menjadi bias dan tidak utuh.
Langkah penulis buku ini, Furida Simanjuntak, mengkaji konflik 1992-1998 dan resolusi konflik 1998-2000 menarik dicermati. Dia menghimpun dan mengolah data-data primer dari dokumen-dokumen HKBP kedua belah pihak dalam format notulen rapat atau pertemuan, laporan-laporan, surat-surat, dan bahan dokumentasi tertulis lainnya.
Memang buku ini tidak mengungkap lebih jauh fakta di balik dokumen-dokumen tertulis. Tapi hanya menggunakan studi literatur. Kendati begitu, berdasarkan dokumen dari kedua pihak, kajian ini menyingkapkan dengan jelas bahwa ada jejak pemerintah Orde Baru mengintervensi dan bermain dalam konflik HKBP.
Tentu studi ini masih merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan menggali data dan informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dan resolusi konflik HKBP.
Penerbitan hasil penelitian ini dalam bentuk buku tentu saja akan mengundang diskusi lebih lanjut. Diharapkan ada rumusan resolusi yang lebih konkret untuk menghapus jejak dan menyembuhkan dampak konflik yang telah. Potensi konflik memang akan selalu ada, tapi sejak awal pimpinan dan jemaat harus memiliki kemampuan mengelolanya agar tidak mudah terpengaruh menjadi destruktif.(*)
Medan, 18 Juli 2012
NB. Tulisan ini merupakan Prolog dalam buku berjudul "Gereja Batak dan Politik Kekuasaan" yang ditulis Furida Simanjuntak, dan editor Sahat P. Siburian, yang diterbitkan LAPiK, 2012.